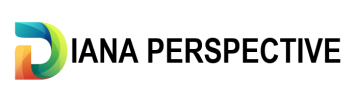Kerentanan Terstruktur di Balik Nama Baik Kampus
Kampus semestinya menjadi ruang aman bagi setiap mahasiswa—ruang di mana kebebasan berpikir dan ekspresi kritis dirayakan, bukan dibungkam. Dalam idealnya, kampus bukan hanya tempat memperoleh gelar akademik, tetapi juga laboratorium sosial tempat mahasiswa menempa jati diri, memperluas horizon intelektual, dan belajar membangun relasi yang setara dan manusiawi. Namun, kenyataan di berbagai perguruan tinggi menunjukkan sisi yang berlawanan. Dalam beberapa tahun terakhir, marak terungkap kasus kekerasan seksual, pelecehan verbal dan fisik, hingga represi terhadap ekspresi politik mahasiswa.
Kekerasan yang terjadi di ruang akademik bukan sekadar tindakan individu, melainkan mencerminkan sistem yang permisif terhadap penyalahgunaan kuasa. Dosen atau mahasiswa senior yang seharusnya menjadi pendamping akademik justru kadang menjadi pelaku, dilindungi oleh struktur institusi yang lebih mementingkan reputasi daripada keadilan bagi korban. Ketimpangan relasi ini diperparah oleh budaya diam—di mana korban dipaksa untuk menahan luka demi menghindari stigma sosial, nilai akademik yang terancam, atau cemooh dari sesama sivitas akademika.
Situasi ini bukan hanya mengganggu rasa aman mahasiswa perempuan, tetapi juga melemahkan prinsip dasar pendidikan tinggi sebagai arena pembebasan. Ketika kampus gagal menjadi tempat yang inklusif dan setara, maka yang tercipta bukanlah ruang kritis, melainkan ruang penuh kecemasan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, penting untuk melihat kembali bagaimana struktur, budaya, dan kebijakan kampus dapat membentuk iklim yang aman, atau justru sebaliknya—menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
Fenomena ini bukan sekadar wacana normatif atau spekulasi teoritis. Ketika prinsip prinsip dasar kampus sebagai ruang aman dan setara dikhianati oleh praktik kekerasan seksual, maka urgensi untuk membongkar sistem yang membiarkannya menjadi tak terbantahkan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kampus di Indonesia menjadi sorotan akibat terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan aktor dari berbagai jenjang. Di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, seorang oknum guru besar diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelecehan terhadap sejumlah mahasiswi dalam periode 2023–2024 [1]. Sementara di Padang, dua oknum mahasiswa dari Fakultas Kedokteran diberhentikan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa yang melibatkan belasan korban [2]. Di Depok, seorang ketua organisasi kemahasiswaan dijatuhi sanksi skorsing setelah terbukti terlibat dalam kasus kekerasan seksual—namun penanganannya dikritik publik karena dinilai minim transparansi dan terlalu lunak [3]. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak mengenal batas peran—baik dosen, mahasiswa senior, maupun sesama rekan sejawat bisa menjadi pelaku—dan bahwa sistem perlindungan di kampus masih jauh dari kata memadai.
Apa yang tampak sebagai tindakan individu ternyata berakar pada persoalan struktural yang lebih dalam. Ketidakmampuan institusi pendidikan tinggi dalam membangun mekanisme pencegahan yang kuat serta budaya kampus yang suportif bagi korban memperlihatkan adanya kegagalan sistemik. Ketiadaan transparansi, minimnya akuntabilitas internal, serta dominasi relasi kuasa vertikal telah menciptakan ekosistem yang membiarkan kekerasan seksual terus berulang. Karena itu, solusi tidak bisa berhenti pada penindakan kasus demi kasus; dibutuhkan pendekatan transformatif yang menyasar akar persoalan melalui reformasi kebijakan kelembagaan dan pergeseran budaya akademik ke arah yang lebih adil, aman, dan berpihak pada korban.
Faktor-Faktor Struktural dalam Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik
Untuk memahami mengapa kekerasan seksual di kampus kerap tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara layak, kita perlu menelaah lebih dalam sejumlah faktor struktural yang secara sistematis memungkinkan kekerasan itu terjadi dan bertahan. Setidaknya ada tiga aspek utama yang menjadi penyumbang signifikan dalam persoalan ini.
1. Relasi Kuasa
Salah satu aspek yang memperkuat dinamika ini adalah relasi kuasa. Ketimpangan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang [4]. Dosen, sebagai figur otoritas dengan kontrol signifikan atas penilaian akademik dan peluang penelitian, dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan pelecehan seksual [5]. Mahasiswa sering kali merasa tertekan atau takut untuk melaporkan insiden tersebut karena khawatir akan dampak negatif terhadap pendidikan dan karier mereka. Penelitian oleh McLaughlin, Uggen, dan Blackstone (2012) menyoroti bahwa kekuasaan merupakan elemen sentral dalam teori feminis mengenai pelecehan seksual, di mana ketidakseimbangan kekuasaan memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual di tempat kerja, termasuk di lingkungan akademik [6].
2. Budaya Diam
Tak kalah penting adalah budaya diam yang menutupi kasus-kasus tersebut. Stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan dampak akademik menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak mengungkapkan pengalaman mereka [7]. Budaya diam ini diperkuat oleh kurangnya respons institusi yang mendukung, sehingga korban merasa tidak ada gunanya melapor [8]. Sebuah studi yang diterbitkan di PLOS One mengungkapkan bahwa meskipun gerakan #MeToo telah menantang ‘budaya diam’ terkait pelecehan seksual, masih terdapat sedikit penelitian mengenai fenomena ini di lingkungan akademik, menyoroti perlunya perhatian lebih lanjut terhadap isu ini [9].
3. Lemahnya Mekanisme Pelaporan
Selain aspek sosial dan psikologis, hambatan struktural juga tercermin dalam lemahnya sistem pelaporan di banyak institusi pendidikan tinggi. Tidak semua kampus memiliki prosedur pelaporan yang jelas, aman, dan mendukung keberanian penyintas untuk bersuara. Meski Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) telah dibentuk di sejumlah universitas, fungsinya sering kali hanya bersifat administratif tanpa dilengkapi layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau akses advokasi yang memadai [10]. Akibatnya, banyak penyintas enggan menyampaikan laporan karena merasa proses yang tersedia tidak akan menjamin perlindungan ataupun keadilan. Penelitian oleh Nengyanti dan Sari (2023) menunjukkan bahwa efektivitas satgas kekerasan seksual masih minim dan memerlukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan maupun implementasinya [11].
Intervensi Terpadu untuk Membangun Ruang Akademik yang Aman
Upaya menciptakan kampus yang aman tidak bisa dilakukan secara parsial atau simbolik. Diperlukan serangkaian intervensi terpadu—baik secara edukatif, struktural, maupun kultural—yang dapat mengubah ekosistem akademik secara berkelanjutan.
1. Pendidikan Kesadaran Gender dan Anti-Kekerasan
Menyelenggarakan program pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan bagi seluruh sivitas akademika sangat penting. Program seperti “The World Starts With Me” di Uganda telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran dan mengurangi perilaku kekerasan seksual di kalangan remaja [12].
2. Sistem Pelaporan dan Pendampingan Korban yang Efektif dan Rahasia
Membangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses, terpercaya, dan menjaga kerahasiaan korban adalah krusial. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual di kampus tidak dilaporkan karena korban merasa tidak ada sistem yang mendukung [13]. Menyediakan layanan pendampingan psikologis dan hukum yang memadai dapat mendorong korban untuk berani melapor.
3. Sanksi Tegas dan Transparan kepada Pelaku, Tanpa Kompromi Jabatan
Penerapan sanksi yang konsisten dan transparan terhadap pelaku kekerasan seksual, tanpa memandang posisi atau jabatan, penting untuk menciptakan efek jera. Studi menekankan bahwa ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus dapat memperburuk budaya impunitas [14] .
4. Solidaritas Horizontal Antar Mahasiswa agar Korban Tidak Merasa Sendiri
Membangun jaringan dukungan antar mahasiswa dapat membantu korban merasa didukung dan tidak terisolasi. Gerakan solidaritas, seperti aksi “walk out” yang dilakukan mahasiswa Queen’s University, menunjukkan bagaimana dukungan kolektif dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan moral kepada korban [15].
Implementasi keempat langkah ini secara terpadu dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika.
🔁 Penutup
Kampus tidak semata-mata berfungsi sebagai ruang transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai ruang hidup yang seharusnya menjamin keselamatan, kesetaraan, dan keberdayaan seluruh warganya. Ketika institusi pendidikan lebih memilih menjaga citra ketimbang keadilan, maka korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan ganda, tetapi juga terperangkap dalam sistem yang abai. Sudah saatnya relasi kuasa yang timpang dan budaya diam dibongkar melalui pendekatan struktural dan kultural yang serius. Ruang akademik harus direklamasi sebagai tempat yang bebas dari ketakutan—tempat di mana pengetahuan dan keberanian dapat tumbuh secara setara.
Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua ketimpangan hari ini. Tapi kita bisa mulai dengan satu hal sederhana: berhenti diam. Dan dari sana, membangun kampus yang tidak hanya mencerdaskan, tapi juga melindungi.
Referensi
[1] H. Firdaus, “Kronologi Pemecatan Guru Besar Farmasi UGM Terkait Kasus Kekerasan Seksual,” Kompas.id. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.kompas.id/artikel/kronologi-pemecatan-guru-besar-farmasi-ugm-terkait-kasus-kekerasan-seksual
[2] Y. Sastra, “Rektor Unand Berhentikan Dua Mahasiswa Kedokteran Tersangka Pelecehan Seksual,” Kompas.id. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/07/rektor-unand-berhentikan-dua-mahasiswa-kedokteran-tersangka-pelecehan-seksual
[3] R. Juliansyah, “Ketua BEM UI 2023 Melki Sedek Huang Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual, Ini Kata Humas Universitas Indonesia,” tempo.co. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.tempo.co/hukum/ketua-bem-ui-2023-melki-sedek-huang-terbukti-lakukan-kekerasan-seksual-ini-kata-humas-universitas-indonesia–92042
[4] C. Vanner, A. Holloway, and S. Almanssori, “Teaching and learning with power and privilege: Student and teacher identity in education about gender-based violence,” Teach. Teach. Educ., vol. 116, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103755.
[5] F. Bondestam and M. Lundqvist, “Sexual harassment in higher education – a systematic review,” Eur. J. High. Educ., vol. 10, no. 4, pp. 397–419, 2020, doi: https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833.
[6] H. McLaughlin, C. Uggen, and A. Blackstone, “Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power,” Am. Sociol. Rev., vol. 77, no. 4, pp. 625–647, 2012, doi: https://doi.org/10.1177/0003122412451728.
[7] N. Achmad, H. Susanto, D. D. Rapita, and F. Fatmariza, “Shame culture and the prevention of sexual harassment in university: A case study in Indonesia,” Res. J. Adv. Humanit., vol. 4, no. 4, 2023, doi: 10.58256/g7ms0h54.
[8] T. Wright, “In-Service Rape and Sexual Assault: A Form of Social Death for UK Service Personnel,” Forward Assists Weekly Blog. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.forward-assist.com/blog/2025/2/11/in-service-rape-and-sexual-assault-a-form-of-social-death-for-uk-service-personnel
[9] C. Canivet, U. Andersson, and A. Agardh, “What determines the ‘culture of silence’? Disclosing and reporting sexual harassment among university employees and students at a large Swedish public university,” PLoS One, vol. 20, no. 3, 2025, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319407.
[10] Admin Undiknas, “Exploring the Important Role of the PPKS Task Force: Preventing and Handling Sexual Violence in Higher Education,” https://undiknas.ac.id/. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://undiknas.ac.id/en/2023/12/exploring-the-important-role-of-the-ppks-task-force-preventing-and-handling-sexual-violence-in-higher-education/#:~:text=Advocacy and Education: The PPKS Task Force,positive perceptions and attitudes regarding sexual violence.
[11] Nengyanti, K. Imania, Yusnaini, and A. D. Santoso, “Institutional isomorphism in policies on sexual violence prevention and management in Indonesian universities,” Issues Educ. Res., vol. 33, no. 2, pp. 673–692, 2023.
[12] L. E. Rijsdijk, A. E. Bos, R. A. Ruiter, J. N. Leerlooijer, and B. De Haas, “The World Starts with Me: A multilevel evaluation of a comprehensive sex education programme targeting adolescents in Uganda,” BMC Public Health, vol. 11, no. 1, p. 334, 2011, doi: 10.1186/1471-2458-11-334.
[13] B. A. Pappas, “How Can We Increase Reporting of Sexual Misconduct on Campus?,” genderpolicyreport.umn.edu. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://genderpolicyreport.umn.edu/how-can-we-increase-reporting-of-sexual-misconduct-on-campus/?utm_source=chatgpt.com
[14] M. Syaifullah, “UGM Dismisses Professor for Committing Sexual Violence as Lecturer,” tempo.co. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://en.tempo.co/read/1993989/ugm-dismisses-professor-for-committing-sexual-violence-as-lecturer
[15] S. Lord, “Walk out in solidarity with survivors of sexual violence,” https://www.queensu.ca/. Accessed: Apr. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.queensu.ca/gnds/walk-out-solidarity-survivors-sexual-violence?utm_source=chatgpt.com